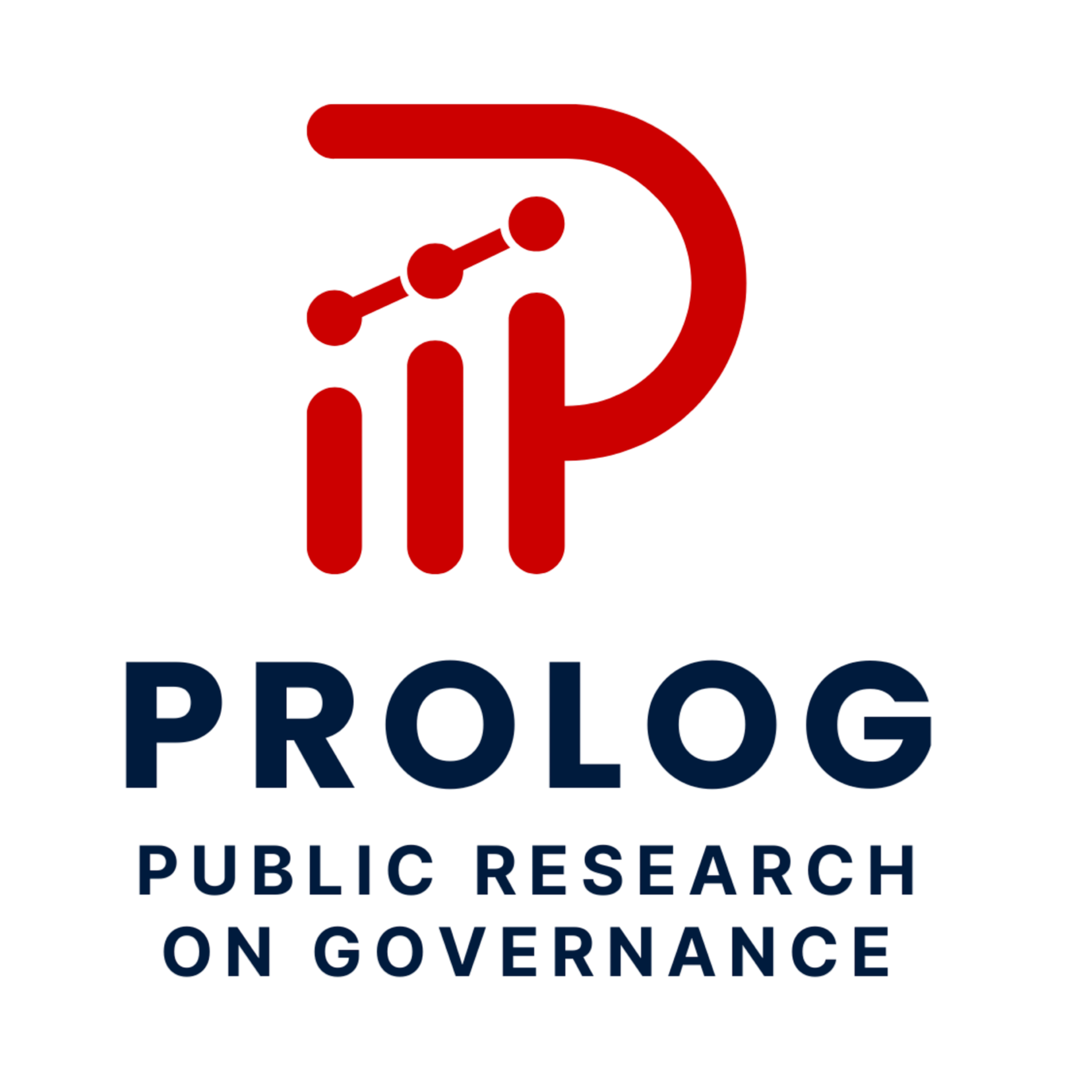Akhir-akhir ini media masa banyak membicarakan perkembangan wajah pendidikan Indonesia. Buntut kasus pemukulan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap siswa yang terdapat merokok yang berujung pada pemecatan yang dilakukan oleh Gubernur Banten. Pemberitaan tersebut ramai di perbincangkan oleh semua kalangan baik pendidik, pemerhati pendidikan dan pengamat pendidikan.
Pendidikan Karakter dan Dilema Hukum
Kasus penonaktifan kepala sekolah Kembali membuka perdebatan tentang batas antar disiplin dan kekerasan dalam dunia pendidikan. Di satu sisi Tindakan kekerasan fisik terhadap siswa bertentangan dengan undang-undang anak dan Permendikbudristek no 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Namun di sisi lain, kita juga harus jujur mengatakan bahwa guru dan kepala sekolah di lapangan kerap berada dalam situasi dilematis ketika berhadapan dengan realitas moral yang jauh lebih kompleks.
Semua orang akan berpandangan bahwa setiap Tindakan kekerasan tidak boleh dibenarkan, namun kejadian ini tidak boleh dipandang sekedar kacamata hukum yang kaku. Kepala sekolah merupakan figur pendidikan yang memikul beban moral dan sosial untuk membentuk karakter siswa. Ketika siswa tertangkap merokok di lingkungan sekolah Tindakan yang jelas melanggar tata tertib reaksi spontan kepala sekolah bisa dimaknai sebagai bentuk keprihatinan dan tanggung jawab moral bukan niat untuk menyakiti. Namun, dimata hukum sering kali gagar menangkap dimensi niat dan konteks moral ini.
Dalam kacamata hukum Tindakan kepala sekolah memang dapat dikategorikan pelanggaran administrasi dan mungkin saja mendapatkan pidana ringan jika memenuhi unsur kekerasan terhadap anak sesuai yang diatur dalam UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun perlu dipahami konteks undang-undang tersebut melindungi anak dari kekerasan yang sistematis dan berulang, bukan menjerat perbuatan spontan yang dilakukan dalam pendidikan moral. Pada posisi seperti ini kita menemukan dilema hukum pendidikan di Indonesia, di satu sisi hukum memberikan perlindungan kepada anak secara absolut, tetapi disisi yang lain tidak memberi ruang yang cukup bagi pendidik untuk menegakkan nilai dan disiplin secara proporsional.
Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter adalah proses Panjang yang menekankan pentingnya menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Dalam teorinya Thomas Lickona (1991) tentang pendidikan karakter, Thomas mengemukakan terdapat tiga pilar utama sebagai berikut; (1) moral knowing merupakan kesadaran dan pemahaman seseorang mengenai nilai-nilai moral yang berlaku. (2) moral feeling berhubungan dengan rasa empati, simpati, rasa malu dan cinta terhadap kebaikan dan (3) moral action adalah merupakan Tindakan yang mewujudkan perilaku, perbuatan dan Tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan rasa hormat. Ketiga pilar diajarkan dengan keteladanan, pembiasaan, dan konsekuensi. Tampa penegasan disiplin yang tegas, moral action hanya akan menjadi wacana. Dalam konteks guru menegur siswanya merokok, sejatinya menjalan tanggung jawab moral sebagai agent of character building, meskipun cara yang ditempuh menyalahi aturan formal.
Kerangka hukum pendidikan kita selalu memandang semua Tindakan hitam dan putih, kekerasan atau bukan kekerasan. Tidak ada yang mempertimbangkan niat, konteks atau bilai edukatif di balik Tindakan tersebut. Jika kita lihat realita di lapangan guru menghadapi tekanan besar seperti tanggung jawab menanamkan karakter, administrasi dan tuntutan public yang sering kali berubah arah sesuai dengan tren media social. Pada akhirnya sekolah menjadi ruang penuh ketakutan, guru takut bertindak, kepala sekolah takut menegur dan akhirnya disiplin berubah menjadi slogan tanpa makna.
Kita sama-sama harus punya kesadaran dan keadilan, Tindakan kekerasan harus kita hindari secara Bersama tetapi kita harus berani berani bersikap adil terhadap pendidik yang beritikad baik. Penonaktifan kepala sekolah semestinya tidak serta merta dianggap bentuk hukuman, melainkan kesempatan evaluasi yang proporsional dan berimbang, pemerintah daerah perlu mengedepankan restorative justice dalam dunia pendidikan, proses ini membuka ruang untuk dialog dan pembelajaran bagi kedua pihak, bukan hanya hukuman sepihak.
Kasus ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk menata ulang relasi hukum, moral dan pendidikan. Negara tidak sekedar membuat regulasi pencegahan kekerasan, tetapi harus ada ketegasan menerapkan restorative bagi seluruh pendidik. Para orang tua, masyarakat harus sama-sama memahami bahwa tanggung jawab pendidikan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada guru atau kepala sekolah tetapi haru menjadi tanggung jawab Bersama.
Pendidikan karakter tidak bisa tumbuh di ruang yang penuh dengan ketakutan hukum, tetapi ia membutuhkan kehangatan, keteladanan dan ketegasan yang manusiawi. Kepala sekolah yang menegur siswa dengan cara yang salah memang harus dievaluasi, tetapi niat moralnya jangan dibunuh dengan birokrasi yang kaku. Kita harus memahami dibalik Tindakan yang tampak keras sering kali ada niat tulus untuk menyelamatkan anak bangsa dari moral yang lebih membahayakan yaitu kelalaian dan ketidakpedulian.
Fitrah
Peneliti Prolog (Public Research on Governance)